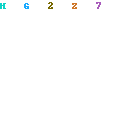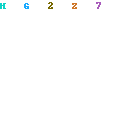Sebenarnya, pria itu tak punya rencana masuk ke Fakultas Kedokteran di UISU—Universitas Islam Sumatera Utara. Tapi, apa boleh buat. Hanya di sanalah ia mampu membiayai diri. Penghasilannya sebagai pramu bungkus di sebuah swalayan ditambah bantuan dari orang tua hanya cukup untuk mengenyam pendidikan di universitas itu. Pria itu memang tak pernah patah arang. Ia akan bekerja apa saja—asal halal—demi mewujudkan cita-citanya sejak kelas 2 SD: dokter.
Suatu hari, datanglah pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu oleh pria itu. “Kenapa pula kau mau kuliah di UISU? Kau bukan seorang Muslim, kan?” tanya seorang mahasiswa yang bernama Rudi Silitonga—mahasiswa yang terkenal kaya di universitas itu. “Agama kau Buddha, kan?”
“Ya, agama saya Buddha dan—maukah kau tidak mengungkit soal agama, Kawan? Kita semua satu, bukan? Kita semua bagian dari Indonesia. Lagipula, saya juga kekurangan biaya. Saya orang susah, kalau boleh jujur—dan saya tidak minta simpati.”
“Hmmm....”
“Tenang, saya juga tidak pernah menggunakan bahasa ibu di hadapan kalian semua. Saya termasuk orang yang menghargai orang lain, kok! Oh, iya... nama saya....”
“Aku sudah tahu nama kau dan nama semua orang non-pri yang masuk UISU,” potong Rudi. “Apalagi, satu kampus memperbincangkan kau, macam mana aku tak tahu nama kau? Mereka bilang kau jenius, tahu?”
“Hei, saya pribumi. Saya lahir di Indonesia, lho.”
“Tapi buyutmu pendatang.”
“Ah, itu omong kosong! Biar kutanyakan padamu, apakah generasi pertama keluargamu lahir di Indonesia?”
“Harusnya begitu.”
“Tak ada yang tahu itu. Yang kutahu pasti, kita orang Indonesia. Jangan kau kira karena mata kakekku sipit, kakekku tidak memerangi Jepang dulu. Justru Beliau mati di tangan Jepang!”
“Oke,” kata Rudi menyerah. “Omong-omong, kau bisa mengerti Pelajaran Agama Islam yang diajarkan? Kau tahu, kan, kalau pelajaran itu termasuk pelajaran wajib dan penentu?”
“Saya yakin orang sepertimu tidak akan membiarkan orang lain kesusahan. Pasti kamu akan mengajarkan saya. Yah, dengan setengah hati, barangkali. Lagipula, saya punya keinginan untuk masuk Islam. Saya sudah disunat, lho!”
Rudi tersenyum.
Dan, mulai saat itu, mereka bersahabat....
Si kaya dan si miskin....
* * *
Tanjungpinang, 1990
Perempuan berseragam SMA itu menggenggam sekepal tepung terigu. ”Lalu, harus aku apakan tepung ini, Ma Magda?” tanya perempuan itu setengah berbisik, seakan ada yang mencuri dengar kata-katanya.
“Tutup matamu, lalu taburkan tepung itu ke atas meja,” jawab Ma Magda dengan suara separau burung kakak tua.
Segera perempuan itu menuruti perintah Ma Magda. Ia memejamkan kedua matanya, lalu menaburkan tepung itu ke atas meja kayu berbentuk lingkaran yang terletak di antara mereka berdua. Ia membuka mata dengan perlahan.
Ma Magda, kemudian, tampak mempelajari ceceran tepung terigu di atas meja. Sorot matanya misterius dan membuat siapa pun merinding. Nenek itu tampak ragu. “Bintang-bintang sepertinya memusuhimu,” katanya. ”Orang tuamu pernah berbuat kejam dengan mereka dan kamu yang harus membayar hutang itu.”
“. . .” Hah?
“Tutup matamu sekali lagi dan buang ludah ke atas serakan tepung itu.”
Sesaat, perempuan itu tampak ragu, tapi kemudian ia segera memejamkan mata, lalu mengumpulkan air ludah di dalam mulutnya dan...
PLEKKK.... Remaja berumur enam belas tahun itu meludahi serakan tepung seperti yang tadi diperintahkan Ma Magda, kemudian membuka matanya perlahan.
“Sekarang aduk tepung dan air ludah dengan jarimu.”
“. . .” Jorok!
“Sekarang!”
“Bintang-bintang tak mau berdamai denganmu. Kamu harus menebus semua dengan kematian. Kamu harus hati-hati dengan enam, enam yang datang dari dalam. Bintang ke-enam punya dendam terbesar. Hati-hati juga dengan Dewa.”
“. . .” Bohong! Sinting!
Seakan bisa membaca pikiran pelanggannya, paranormal blasteran Belanda-Jawa yang baru dua bulan pindah dari Jakarta itu berkata dengan nada tajam, “Kalau kamu katakan saya bohong, tak usah datang sini lagi!”
“. . .” Nenek aneh!
“Kamu yang aneh!”
“. . .” Masa dia bisa tahu apa yang kupikirkan?
“Jelas tahu. Jika tidak, bukan paranormal namanya.”
* * *
Ubud, 1994
Tiap pagi, Komang pasti datang ke warung ini untuk melukis. Begitu pula dengan pagi ini.
“Selamat pagi, Mbak Komang!”
“Wah, jangan Komang lagi, lah, Mas Bram! Panggil nama asli saja.”
“Komang lebih lucu.”
“Ahh...!”
Mas Bram adalah pria keturunan Jawa-Batak, tapi menetap di Bali sejak lahir, karena ayahnya dinas di situ, bahkan sebelum Mas Bram lahir. Usianya 32 tahun. “Komang mau Serombotan dan kopi lagi?”
“Iya. Serombotan saja. Biar—maaf,” ia sedikit berbisik, “buang air besar saya lancar”
“Jorok, ah! Ini warung makan, Komang,” Mas Bram cekikikan. “Komang tidak mau coba makan nasi goreng spesial? Tiap hari sarapan Serombotan, masa tidak bosan?”
“Soalnya campuran buncis, bayam, kangkung, tauge, kecipir, pare, terung, kacang panjang, sambal kelapa, dan sambal koples-nya maut, Mas Bram! Lagipula, untuk apa saya makan nasi goreng? Saya juga bisa masak sendiri, kan?”
“Nah, itu hafal bahan-bahan bikin serombotan,” pemilik warung makan tanpa nama itu tertawa lagi. “Kenapa tidak coba Nasi Be Guling?”
“Saya tidak suka babi.”
“Saya kira orang Cina suka makan babi. Eh, minumnya kopi tubruk pakai kayu manis lagi?”
“Tepat sekali, Mas Bram!” Komang duduk di pojok warung itu, lalu mengeluarkan buku sketsa dan Konte-nya dari dalam tas batik yang ia beli di Yogyakarta dengan harga sangat murah karena proses tawar-menawar yang panjang, seru, heboh, dan melelahkan.
Ia membuka lembar demi lembar buku sketsanya, menikmati lukisannya yang semrawut namun indah.
Kurang dari tiga menit, Mas Bram datang membawa pesanan Komang: sepiring Serombotan dan secangkir kopi tubruk panas dengan kayu manis. Sedap...!
Tanpa ucapan terima kasih—seperti biasa—Komang langsung mengaduk-aduk serombotannya. Lalu, bukannya dimakan, ia malah beraksi dengan Konte dan buku sketsanya.
Sudah bermenit-menit Mas Bram memperhatikan Komang yang terus melukis tanpa mempedulikan serombotannya yang kini sudah dilalati.
Ia menghampiri Komang dan melirik lukisan Komang. “Gambarnya masih corat-coret? Sedari sebulan yang lalu saya perhatikan, lukisannya corat-coret saja. Abstrak, ya?”
“Bukan abstrak,” Komang tak beralih dari buku sketsanya.
“Terus apa?”
“Ini makhluk halus,” Komang meninggalkan kesibukannya dan menatap Mas Bram selama beberapa detik dengan tatapan sinis. Kemudian, “Apa benar tempat ini dulu tanah perkuburan?”
Mas Bram mengernyitkan dahi, bingung, “Hah? Kuburan? Di sini....”
“Saya tahu dan sekarang, saya butuh privasi,” jawab Komang ketus. “Nanti makhluk halusnya pergi kalau Mas Bram tidak menyingkir. Mereka kira Mas Bram dukun.”
“. . .”
Dan, Komang pun melanjutkan kegiatannya, tak peduli akan cacing-cacing di perutnya yang sedang unjuk rasa, minta diberi makanan.
Tak tahukah dia bahwa yang kugambar adalah Serombotan yang dia sajikan?
* * *
Tanjungpinang, 1996
Ketika kami berdua bertemu kembali di kasir, barulah aku tahu kalau Richard—suamiku yang ganteng namun pendek itu—telah membohongi diriku. Tadi saat kami baru memasuki toko buku kecil itu, dia mengusulkan untuk berpencar saja. Dia menyarankanku untuk langsung menuju rak tempat novel-novel karya Mira W. – Marga T. dipajang sementara dia mengaku ingin mencari buku DOI—Data Obat di Indonesia. Kuiyakan saja saat itu karena aku pun tak tertarik dengan buku seperti itu. Maka, aku mengikuti usulnya untuk berpencar; aku mencari novel Mira W. – Marga T. yang belum kubaca, dan Richard mencari buku DOI-nya.
Ternyata apa? Hah, bodohnya aku sampai-sampai mempercayai dia mencari buku DOI yang tebalnya lebih dari 1530 halaman di toko buku sekecil ini! Di genggamannya—dapat kulihat dengan jelas—sebuah buku putih yang tebalnya kira-kira tiga ratus halaman dengan sampul bergambar bayi-bayi yang lucu: NAMA PILIHAN UNTUK BAYI ANDA.
Kulirik buku itu dengan tatapan sok sinis, kemudian tersenyum ke arahnya seraya berkata, “Wah, sampul buku DOI rupanya lucu, ya? Tadi, aku kira sampulnya polos atau bergambar suntik dan obat.”
Richard tersenyum jenaka. Lucu sekali wajahnya seperti itu. “Ini DOI, kok. Maksudnya, Data Orang Indonesia.”
“Leluconmu terlalu dipaksakan!”
“Sebodo!”
Richard pun tertawa, disusul olehku.
“Jadi, kamu benar-benar mau cari nama bayi kamu sekarang?”
“Daripada tidak ada kerjaan, kan?”
“Bukan begitu, sih. Tapi, kan, bayi yang ada di perut aku sekarang belum tentu dapat melihat dunia luar. Bisa saja, kan, aku keguguran?”
“Apaan, sih, kamu? Ngomongnya, kok, begitu?”
“Nah, lho? Lagian, ini bayi juga masih butuh tujuh bulan lagi baru bisa dipeluk.”
“Nah, ini aku peluk, nih!”
“Bukan itu maksudnya. Maksud aku dengan kata ‘dipeluk’ itu....”
“Aku tahu, kok, maksudnya. Aku tidak bodoh.”
“Tersinggung....”
“Eh, namanya Glenn saja, yuk!”
“Ah, aku tidak mau nama yang pasaran buat anak pertama kita, Chad! Sepasang suami-istri yang punya nama pasaran dan sok kebule-bulean sudah cukup. Aku pingin nama anak kita yang keren, yang... kalau bisa dari Bahasa Sansekerta atau yang semacamnya, lah!”
“Jelek, ah!”
“Kamu tidak punya selera! Bule-bule, kan, suka sama orang yang eksotis. Mereka alergi sama nama orang Barat, tahu! Kan, kamu pernah bilang kalau kamu pingin anak kamu nikah sama bule untuk memperbaiki keturunan.”
“Sok tahu! Kalau bule suka sama nama eksotis, kenapa mereka masih pakai nama-nama seperti Madonna dan Mariah Carey?—Scott Glenn dan Jodie Foster?”
“Itu karena nama Ja’far tidak sesuai bila ditambah Franklin, apalagi Holiday di belakangnya. Gwen yang bilang ke aku, kok!”
“Apa? Gwendoline Allain yang bikin kacau resepsi pernikahan kita beberapa bulan yang lalu dengan mengatakan makanan Cina rasanya seperti kardus itu? Wah, tahu apa dia?!”
“Ralat: masakan Cina-Bali. Lagipula, setidaknya, wawasan dia tentang dunia Barat lebih luas daripada orang Cina.”
“Itu, kan, hanya pendapat dia jika nama orang kalau eksotis bakal bagus. Begini, deh, nama seperti itu mudah dicari. Bagaimana kalau kita cari nama Cina anak kita saja duluan?”
“Boleh, boleh!”
“Kalau anak yang di perut kamu cowok, namanya....”
“. . .”
“Lee ....”
“Eh, kok, pakai marga keluarga kamu?”
“Kan, memang peraturannya seperti itu, Sheil.”
“Ah, tidak bisa! Pokoknya harus pakai marga keluarga aku! Harus pakai marga Tan!”
“Sudah ada peraturannya, Sheil. Kamu tidak boleh seenaknya.”
“Kamu egois!”
“Bukan ‘gitu, Sheil. Tapi, kan, kita harus mengikuti garis keturunan ayah.”
“Kamu kuno! Kamu betah hidup dengan mengikuti peraturan?”
“Tanpa peraturan, semua kacau! Bahkan, dengan ada peraturan saja banyak yang melanggar.”
“Oh, ya? Masa? Aku ragu sama omongan kamu!”
“Terserah apa maumu. Adat sudah membenarkan perkataanku.”
“Kalau begitu, aku mau menentang adat!”
“Menentang adat? Kamu pikir, kamu siapa?”
“Aku adalah seorang wanita yang minta didengar. Teriakanku memang kecil, tapi aku yakin aku bisa mengubah semua ketidakadilan ini! Satu tarikan nafas seseorang bisa mengubah dunia, aku yakin itu!”
“Kamu, kok, merajuk kaya bocah ‘gitu?”
“Halah! Kamu saja yang ngiris bawangnya, aku mau istirahat! Capek jadi babu rumah tangga!”
“Aku juga capek tiap hari di kamar praktik, berhadapan dengan pasien tidak punya etika!”
“Dasar kuno! Norak! Zaman sekarang masih nurut sama adat?!”
“Kenapa perempuan jarang diberi kesempatan?”
“Kenapa aku tidak jadi orang Minang saja?!”
“Nyesal aku nikah sama kamu, Chad! Kamu orangnya norak!”
“Suami Gwen saja nurutin kata-kata Gwen buat makai nama keluarga dia saja!”
“POKOKNYA TIDAK ADA KETURUNANKU YANG NANTI BERMARGA LEE, TITIK!”
Kebencianku dengan Chad akhirnya memudar karena akhirnya dia mau membuat sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Bagaimana kalau anak cowok yang lahir, marganya pakai marga keluargaku. Dan kalau anak cewek yang lahir, marganya pakai marga keluarga kamu?”
Dan, aku pun memeluknya.
* * *
Pontianak, Desember 1996
Rio Inggit Darmawangsa, Lee Kuo Chang—buah obsesi Sheila yang pertama, yang dihasilkan dari gabungan spermaku dan ovumnya.
* * *
Singapura, Mei 1998
Billy Dewantara, Lee Kuo Jen—buah obsesi Sheila yang kedua, yang dihasilkan dari gabungan spermaku dan ovumnya.
Kami terpaksa hijrah ke Singapura selama beberapa bulan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yah, meski kata rekan-rekan kerjaku di rumah sakit, dampak kerusuhan belum sampai ke Tanjungpinang. Tapi, apa salahnya sedia payung sebelum hujan?
* * *
Tanjungpinang, Maret 2000
Glenn Arya Trimulya, Lee Kuo Ann—buah obsesi Sheila yang ketiga, yang dihasilkan dari gabungan spermaku dan ovumnya.
“Sheil, aku mau mengubah kesepakatan kita.”
“Maksudnya?”
“Kalau kamu hamil anak ke-empat, meski itu cewek atau cowok, marganya akan pakai marga keluargamu. ‘Gimana?”
“Tidak!”
“Tapi,....”
“Aku wanita kuat. Punya pendirian dan harga diri. Sekali kubilang ‘satu’, akan tetap ‘satu’ sampai aku mati. Tidak ada pergeseran sama sekali, meski sekecil apa pun itu! Adat yang tak adil akan kutentang!”
Jadi, aku harus bagaimana lagi menghadapi istriku yang terobsesi menentang adat?
* * *
Pontianak, Oktober 2002
Gabriel Pierre, Lee Kuo Ming—buah obsesi Sheila yang keempat, yang dihasilkan dari gabungan spermaku dan ovumnya.
Ya, Tuhan, berkahilah aku seorang anak perempuan. Aku sudah jenuh, Tuhan!
* * *
Medan, Desember 2004
Rajaa Ja’far, Lee Kuo Kang—buah obsesi Sheila yang kelima, yang dihasilkan dari gabungan spermaku dan ovumnya.
TUHAN!!!
* * *
Tanjungpinang, Januari 2006
Sial! Kenapa Sheila harus keguguran saat bayi yang dikandungnya adalah bayi perempuan?! Padahal, Sheila sudah sangat bersemangat!
TUHAN, AKU MURKA, TUHAN!!! BERIKANLAH AKU ANAK PEREMPUAN! APA KAU SEDANG MEMPERMAINKANKU? MENGUTUKKU? TUHAN, JAWAB AKU!!! JANGAN CUMA DIAM MEMBISU DAN LARI DARI KESALAHANMU!!!
* * *
Tanjungpinang, Febuari 2008
Pagi....
KRING!!! KRING!!!
Gagang telepon diangkat.
“Halo?”
“Halo. Anu-nya sudah disiapkan.”
“Oke. Bagaimana uangnya?”
“Tidak perlu dikhawatirkan. Pokoknya, nanti malam, kamu ikuti saja minuman yang dia pesan. Nanti, akan kuberikan minuman yang sudah diberi anu.”
“Saya minta bonus. Dan, kalau sampai saya kena penyakit, lihat saja nanti!”
“Kerjakan tugasmu serapi mungkin dan kau akan kuberi bonus dua kali lipat dari yang minggu lalu aku tawarkan.”
Dan, sambungan terputus.
Siang....
TLULULUT... TLULULUT...
Gagang telepon diangkat.
“Halo?”
“Anda mengangkat telepon ini untuk mendapat jawaban.”
“Jawaban? Ini siapa, ya?”
“Anda tidak akan menyesal. Ini tentang kebejatan suami Anda.”
“Maksud Anda apa? Siapa Anda?”
“Volcano Pub. Jam sembilan malam. Suami Anda tidak akan pulang malam ini karena dia akan bersenang-senang dengan wanita lain.”
Dan, sambungan terputus.
Malam....
Aku hanya bisa meronta sebisaku. Tapi, tenagaku seakan terkuras habis. Aku tak bisa berbuat apa-apa demi menjaga milik-ku yang sebentar lagi akan dirampas entah siapa dan dari mana. Tuhan, tolong aku! Bagaimana bisa milik-nya begitu mengerikan?! Ya, Tuhan....
* * *
Tanjungpinang, Desember 2008
Kirana Ayu Lestari Indraningsih, Tan Mei Yen—buah obsesi Sheila yang terakhir, yang dihasilkan dari sperma seorang pria dan ovumnya. Pria itu bukan aku. Aku tahu itu. Pria itu rekan kerjaku, Andry Tan. Dia sendiri yang memberitahuku.
Aku... sangat... membenci... Kirana!
Aku... sangat... membenci... Andry!
Aku... juga... sangat... membenci-Nya!
* * *
Pontianak, Januari 2009
Mati....
Mayat....
Krematorium....
Api....
Membara....
Jadi abu....
Rumah abu....
Tahun baru tanpa Mama....
Tak heran Papa begitu membenci Kirana, adik bungsu Rio. Rio juga benci banget sama Kirana karena Kirana sudah bunuh Mama waktu dia dilahirkan. Padahal, kata Papa, Kirana bukan adik kandung Rio.
Suatu saat, aku pasti bunuh Kirana. Adik-adikku yang lain juga berjanji mau bantu Rio bunuh Kirana. Lihat saja nanti!
* * *
Tanjungpinang, 2010
“Pa, ‘napa Kirana Tan, tapi koko Kirana Lee?”
“Karena kamu anak setan!”
“. . .”
* * *
Medan, 1995
Si kaya dan si miskin...
“Bulan depan, aku ulang tahun. Aku mau rayakan di Ubud. Di Bali. Kau harus ikut.”
“Tapi, saya tidak punya biaya, Rudi.”
“Biar saya biayai.”
“Tapi, kuliah?”
“Bulan depan, kan, libur Natal. Eh, lagipula, bukannya kita tinggal antri ujian saja? Jangan mengelabuiku. Aku tak lupa, Kawan!”
“Boros sekali kamu. Masa ulang tahun saja sampai pergi ke Bali?”
“Pokoknya kau harus ikut. Habis perkara!”
* * *
Ubud, 1995
Setahun sudah Komang nongkrong di warung Mas Bram sambil melukis serombotan. Namun, hari ini, tampaknya ada yang berbeda dengan obyek lukisan Komang. Kali ini yang digambarnya bukanlah Serombotan alias “makhluk halus”, melainkan...
“Bukan makhluk halus lagi?”
“Bukan, Mas Bram,” jawab Komang. “Makhluk halus telah dimusnahkan oleh ‘Sang Dewa’ yang duduk di pojok sana dengan temannya.”
Mas Bram menoleh ke pojok warung. Tampak di sana seorang pria beretnis Tiong Hua dan seorang lagi pria keturunan Batak. Mereka sedang menikmati sarapan mareka. “Sedang kasmaran, rupanya.”
“Di antara pengunjung warung ini, hanya mereka yang datang dengan motor, kan?”
Mas Bram menengok halaman warung itu. “Ya. Cuma ada satu motor di halaman dan pengunjung warung ini hanya kamu dan mereka. Berarti, itu motor mereka kalau itu bukan motormu.”
“Dan, saya yakin kalau Mas Bram ingin saya mendapatkan kekasih, kan?”
“Saya cemburu,” Mas Bram tertawa sendiri mendengar leluconnya. “Ya. Saya pasti mau membalas kebaikan Komang yang setengah tahun lalu mencomblangkan saya dengan bidadari cantik yang sekarang sedang bunting.”
“Sini,” dan Komang pun membisikkan sesuatu di telinga Mas Bram. Kemudian, Mas Bram tersenyum, semangat empat-lima membara di dalam dirinya.
Waktunya membalas kebaikan Komang. Pak Comblang memang tugasku sedari dulu. Ah...!
Komang melahap serombotannya dengan cepat, lalu meneguk kopinya hingga habis. Kemudian, cepat-cepat ia berjalan pulang, tanpa membawa buku sketsanya. Buku sketsanya sengaja ia tinggalkan di atas meja.
Langkah pertama.
Mas Bram mengintip ke halaman depan. Komang sudah tak terlihat. Mas Bram segera beraksi. Ia menghampiri meja Komang dan mengambil buku sketsanya yang sengaja ditinggal. Kemudian, ia berjalan perlahan menuju arah ‘Sang Dewa’ di pojok warung.
“Mas, maaf mengganggu. Saya lihat hanya kalian yang datang dengan sepeda motor. Mungkin, kalian mau mengembalikan buku sketsa ini pada wanita yang meninggalkannya. Buku sketsa ini sangat berarti untuknya.”
“Aku tak tahu alamatnya. Lagipula, mungkin saja besok dia datang kemari, kan? Kalau kau sudah tahu buku itu berarti untuk wanita itu, berarti kalian sudah saling kenal. Dia akan datang besok,” pria Batak itu berbicara. Ia tampak tak senang dengan gangguan itu.
“Saya punya alamatnya.”
“Sudah, kau sa....”
“Oh, iya, Mas. Mas berikan alamatnya dan nanti saya usahakan mengembalikan bukunya,” ujar ‘Sang Dewa’.
Pria Batak melotot pada temannya.
“Terima kasih. Saya tulis dulu alamat kontrakannya. Sebentar, ya?”
Sepeninggal Mas Bram untuk menulis alamat kontrakan Komang di meja resepsionis, ‘Sang Dewa’ berkata, “Kalau kamu keberatan, biar saya jalan kaki saja.”
“Oh, tak usah, lah. Kita pergi sama-sama saja.”
Mas Bram tersenyum dalam hati.
Misi saya berhasil. Sekarang tinggal bagaimana cara Komang melepas keperawanannya saja.
TOK... TOK... TOK...
Pintu dibuka dari dalam. Komang—hanya memakai celana dalam beige dan kaos melar khas Bali.
“Sudah kuduga, pasti ‘Dewa’-ku yang datang memberikan bukuku.”
“Saya buru-buru. Ini bukumu. Lukisan Serombotan-mu bagus”
Satu tahun Mas Bram melihat lukisanku, tapi tak mengerti kalau itu lukisan Serombotan. Tapi pria ini....
‘Sang Dewa’ berbalik, hendak pergi. Tapi,...
Komang segera menahan ‘Sang Dewa’ dengan memegang tangannya yang kekar, kemudian berkata, “Siapa nama teman kamu itu?” ia menunjuk ke pria yang duduk di jok motornya.
“Rudi. Ada apa?”
“RUDI,” seru Komang, membuat Ilman nyaris jatuh dari motornya karena terkejut. “RUDI, AKU YAKIN TEMANMU INI PUNYA NYALI UNTUK PULANG SENDIRI. DAN, AKU JUGA YAKIN KALAU DIA BERANI MELEPAS KEPERAWANANKU!” Komang kembali menatap ‘Sang Dewa’ yang ternganga, “Kondom sudah disiapkan. Ada di dalam kamar.”
Satu tahun kemudian, Komang dan ‘Sang Dewa’ melangsungkan pernikahan. Undangan telah disebar ke sanak-saudara dan para sahabat. Resepsi dilaksanakan di warung Mas Bram dan istri yang dikawininya satu setengah tahun lalu (berkat kerja keras Komang)—Gwen—dengan masakan peranakan Cina-Bali yang rasanya memang seperti kardus.
Menikah:
Richard Lee
dengan
Sheila Tan
* * *
Kisaran, 2010
“Aku tahu siapa yang berada di belakang layar.”
“Hmmm...?”
“Aku tahu siapa yang membayar Andry untuk menghamili istriku.”
“. . .”
“Dan, kini kau terdiam? Kau tak menyangka akan ketahuan?”
“Maafkan aku, Kawan. Aku tak tahu istrimu akan meninggal saat melahirkan bayi itu.”
“Maaf? Seingatku, kau adalah orang yang paling membenci kata itu.”
“Jadi, aku harus berbuat apa?”
“Tidak harus berbuat apa-apa. Tapi, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu.”
“Apa?”
“Apakah benar, tujuanmu menyuruh Andry memperkosa istriku adalah supaya aku minta cerai dengannya? Supaya kau yang jatuh cinta padaku bisa berdua denganku? Kau tak rela bila aku bersama dengan Sheila?”
“. . .”
“Kenapa kau diam?”
“Karena, kau sudah tahu jawabannya. Kau memang selalu tahu aku. Jadi, apa salahnya kita bersatu?”
“Oke. Kau memang gay. Kuhargai kejujuranmu. Omong-omong, aku juga ingin mencoba tidur dengan pria. Apa kau mau, Rudi?”
“Tentu! Ini yang kutunggu-tunggu! Tapi, bukankah sebaiknya kita lakukan di apartemenku, di Jakarta?”
“Baiklah!”
“Tiket ke Jakarta akan kupesan besok.”
“Biar aku saja yang bayar. Saatnya membalas kebaikanmu lima belas tahun lalu, ketika kamu membiayai tiket pesawat saya ke Bali.”
* * *
Air Sena, 2010
Aku sedang menyalin sebuah artikel pendek tentang pembunuhan dari koran ketika ibuku yang bawel melolong lagi (mungkin dari dapur karena tercium bau terasi) memecahkan gendang telinga, “JAKI, TOLONG EMAK!!! BOCO!!!1
“AOK, LAH, MAK!2
JAKARTA – Rudi Silitonga (43) di temukan ditemukan tewas di apartemennya yang terletak di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Korban tewas dengan 6 luka tusuk dan tanpa di balut dibalut sehelai benang pun. Pihak kepolisian yang tiba di
Tanjungpinang, Januari 2010
(Terima kasih kepada Dewi Kharisma Michellia untuk semua tentang Bali-nya,
Yen Cecilia untuk nama-nama Mandarinnya,
dan Evi Rahayu untuk Bahasa Air Sena-nya.)
1
2